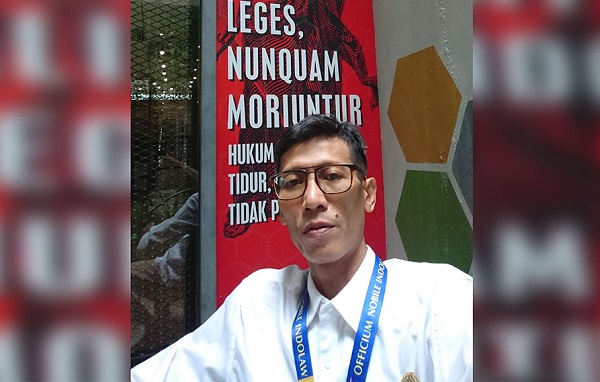Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 disahkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021. Keberadaan peraturan menteri ini mendapat kritik dari banyak pihak, bahkan menjadi polemik karena dianggap memasukkan hal-hal yang berlawanan dengan etika, agama dan budaya.
Kekerasan seksual dirangkaikan dengan frasa "tanpa persetujuan korban" sebagaimana dalam Pasal 5 yang membentuk opini terbatas, sempit dan secara psikis menjadi pokok perdebatan. Demikian juga dengan ayat (3) pasal yang sama bila dipahami secara keliru maka seolah menggugurkan ketentuan lainnya.
Consent tersebut dipahami melegalkan seks bebas dan perilaku menyimpang LGBT di lingkungan kampus asalkan dilakukan dengan persetujuan dan suka sama suka, dan menjustifikasi parameter integritas peraturan menteri tersebut hanya pada persetujuan para pihak, sehingga keluar dari nilai agama dan moralitas. Intinya, peraturan menteri tersebut menimbulkan kesan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas dengan berbasis pada consent atau persetujuan dari para pihak yang terlibat.
Meluruskan Persepsi
Pelaksana tugas (Plt.) DirJen Dikti Ristek, Prof Nizam, mengatakan anggapan itu timbul karena kesalahan persepsi. Karena rancangannya adalah untuk meningkatkan keamanan lingkungan kampus dari kekerasan seksual dan mempertajam literasi masyarakat umum akan batas-batas etis berperilaku di lingkungan Perguruan Tinggi, serta konsekuensi hukumnya.
Consent dalam isi beleid tersebut mengacu pada unsur pemaksaan terkait suatu tindak kekerasan dengan merujuk pada KBBI yang mana kekerasan adalah sesuatu yang dipaksakan atau ada unsur pemaksaan. Jadi, kata consent tersebut dalam konteks unsur pemaksaan, dalam hal ini terutama dalam relasi kuasa dan/atau gender.
- Tholabi Kharlie, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta berpendapat bahwa frasa "tanpa persetujuan korban" jangan dipandang sempit sekadar hubungan yang tanpa ikatan sah karena bisa jadi merupakan "kejahatan seksual" yang saat itu disetujui oleh korban, yang di kemudian hari akan menjadi penyesalan dan trauma.
Kemudian Abdul Fickar Hadjar, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti turut berpendapat dari aspek hukum acara pidana yang mana peraturan menteri tersebut tak dapat mengatur fungsi penindakan dan tidak sampai pada ranah sanksi pidana. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki misi pendidikan, namun ketika ada pelanggaran, maka kampus pun memiliki misi penegakan hukum.
Consent Penting
Mari kita perhatikan dengan baik tentang apa yang menjadi consent dari peraturan menteri tersebut yang lepas dari perhatian, antara lain:
- Dalam perilaku yang berhubungan dengan seksualitas objek seksual dalam peraturan menteri tersebut baik dengan persetujuan maupun tidak namun objek seksual tetap disebut sebagai “korban”;
- Bahwa ide terpenting dan kekuatan Permendikbudristek ini adalah pada frasa "ketimpangan relasi kuasa/gender";
Menurut Penulis, sudah ada pasal-pasal yang harusnya menjadi batasan penentu dalam memahami keseluruhan isi dari peraturan tersebut sehingga tidak keluar dari original intent secara sistematis. Pasal 1 angka 1 memberikan tekanan pada setiap perilaku seks tidak boleh terjadi dalam ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, jangan dipahami sebagai seks bebas di lingkungan kampus. Akan tetapi juga terhadap pasangan suami/isteri yang masih mahasiswa maupun pasangan sah di lingkungan kampus.
Hubungan seksual hanya dapat terjadi ketika terjadi kesetaraan kuasa ataupun kesetaraan gender, tidak ada yang saling menguasai. Sehingga harus dipahami kesepakatan atau persetujuan antar individu tersebut harus dilakukan oleh subjek yang saling setara dalam hak dan kewajiban, bukan sama.
Dalam konteks seksualitas, hal yang diterima umum dan tentunya kesetaraan dalam hukum hanya bisa dicapai ketika terjadi ikatan perkawinan (nikah) antara lelaki dan perempuan, kelamin yang berbeda, dan gender yang setara (maskulin-feminin) yang harus dibedakan dengan makna gender yang sama.
Mengenai uraian dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi, “Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban, dst”, dimaknai bahwa meskipun ada persetujuan namun perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai kekerasan karena penyebutan objek yang menyetujui disebut sebagai “korban” dengan tidak menyebutnya dengan kata “orang”. Dalam kriteria yang disebut dalam Pasal 5 ayat (3) maka perbuatan pelaku masuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam UU lainnya yang bekerja di lingkungan manapun termasuk kampus. Demikian juga Pasal 1 angka 2 memberikan definisi tentang korban.
Peraturan tersebut tidak bisa dan tidaklah ditujukan untuk menghalangi UU lain dan/atau peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Inilah yang akhirnya lepas dari pemikiran karena terlalu fokus mengkritisi.
Tidak Ada yang Keliru, Hanya Salah Paham
Peraturan tersebut jelas melindungi secara preventif. Karena bagaimanapun persetujuan itu ada dengan persepsi (menyimpang) dapat menghalalkan perilaku seksual bebas yang bertanggung jawab namun tetap mempunyai kemungkinan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yaitu bentuk kekerasan, sebagai suatu daya paksa yang tidak diinginkan yang menunjuk pada adanya “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender”.
Artinya peraturan ini justru menutup celah perilaku LGBT dan seks bebas, yang oleh karenanya melalui peraturan ini diharapkan tidak lagi ada perilaku seks bebas dalam lingkungan kampus. Lingkungan kampus juga secara luas meliputi tempat kos dan kontrakan atau yang disamakan dalam konteks relasional kampus.
Sebagaimana dalam hubungan suami-isteri maka terdapat kesetaraan kuasa, dan apa yang berkaitan dengan terminologi setara dalam konteks gender adalah maskulin dengan feminin. Terminologi setara juga harus dibedakan dari penafsiran sama/kesamaan/mirip/serupa secara fisik.
Konteks setara dalam hukum tidak dapat dimaknai sebagai bebas atau suka sama suka akan tetapi sejajar, sama tingkatnya, sebanding, sepadan, seimbang, sederajat serta diakui oleh negara karena mempunyai kepastian hukum. Kesetaraan sebagai lawan dari ketimpangan disebutkan dalam Pasal 2 huruf b, Pasal 3 huruf b dan c, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf d.
Konsep dan pengakuan kesetaraan relasi gender secara filosofis hanya dimungkinkan pada situasi perbedaan kelamin, dan tidak akan terjadi pada kelamin yang sama, karena kesamaan tersebut tetap mempunyai potensi dan manfaat yang sama meski merasa berbeda gender. Namun, Penulis tidak akan membahas lebih jauh karena dapat keluar dari konteks hukum meski berkaitan erat. Dengan demikian adalah keliru bila beranggapan bahwa Permendikbudristek ini melegalkan seks bebas maupun LGBT.
Ekuivalensi Konsep Hukum
Dalam hukum perdata kita juga mengenal konsep yang ekuivalen yaitu “misbruik van omstandigheden”, penyalahgunaan keadaan, cacat kehendak, keadaan tidak seimbang. Dalam hal ini ada kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan namun ada keterpaksaan yang menyebabkan cacat hukum.
Bahwa hubungan seksual yang tidak perlu diatur dalam peraturan menteri ini adalah pola hubungan dalam kesetaraan kuasa/gender dalam ikatan perkawinan yang legal dan kejahatan seksual. Oleh karena itulah peraturan menteri tersebut secara relevan merangkai kalimat yaitu “persetujuan korban”. Mengenai hal ini sebetulnya selalu dibahas dalam viktimologi, hubungan sebab-akibat karena interaksi antara pelaku dengan korban, causa prima (utama) ataupun causa proxima (terdekat).
Dalam hal ini penyebutan korban menurut Penulis lebih dikarenakan telah berlaku sebagai subjek yang menerima perlakuan. Namun secara hukum tidak dalam keadaan yang seimbang sehingga meskipun memiliki pengaruh dalam kausalitas tetap disebut sebagai objek kekerasan yang relatif tapi objektif harus mendapat prioritas perlindungan hukum.
Tafsir Legalitas Seks Bebas dalam Permendikbudristek
Dalam dunia hukum, kita tahu bahwa terdapat metode penafsiran hukum, yaitu tata bahasa (gramatikal), sahih (autentik/resmi), historis, sistematis, nasional, teleologis (sosiologis), ekstensif, restriktif, analogis, a contrario dan lainnya. Tampaknya terjadi blunder antara kritik gramatikal dengan teleologis ataupun sosiologis sehingga sulit diterima ketika tidak mengajukan redeneering acontratio (pertentangan) yang relevan, di mana alas argumentasinya terlalu meluas pada kenyataan penyakit masyarakat yang dihadapi – semoga bukan sentimen – yang berada di luar jangkauan pengaturan peraturan menteri ini apalagi sudah diatur dalam banyak UU.
Permasalahan dasarnya justru pada perkembangan pemikiran dan perilaku masyarakat itu sendiri yang berpotensi mengubah makna frasa “relasi kuasa dan/atau gender”. Masyarakat jangan membuat dugaan bahwa peraturan menteri ini menjadi pintu masuk seks bebas, karena menurut Penulis ia sudah tepat dan evolutif. Dengan demikian, seperti biasanya kita selalu punya tugas memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat – terutama kalangan kampus – mengenai perilaku-perilaku yang menyimpang menurut kaidah agama dan etik agar tidak mudah meracuni kehidupan masyarakat kita.
Dibutuhkan kesepakatan dari para public figure (pejabat), role model (tokoh masyarakat) dan center of interest (kalangan seniman, selebriti dan influencer) untuk menyaring ide-ide HAM yang tidak sesuai dengan kaidah agama, etika dan budaya bangsa dari upaya penetrasinya yang merusak pola pikir masyarakat yang mengakibatkan terganggunya tatanan kemasyarakatan.
Kedudukan Permendikbudristek
Peraturan menteri sama sekali tidak mengatasi UU yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan maupun kejahatan seksual dengan sifat yang memaksa (dwingend). Ia tidak mengikat secara umum (algemeen bindende) dan ditujukan kepada persoon yang membuat ketimpangan relasi kuasa/gender [Pasal 1 ayat (1)] di lingkungan Perguruan Tinggi [Pasal 1, 2 dan 4] serta bersumber dari kekuasaan eksekutif.
Namun harus diakui bahwa terdapat kekurangan dalam konsiderans dengan tidak menyebut UU ITE dan Pornografi. Konsiderans yang memuat ketentuan-ketentuan yang identik berkaitan dengan kedua UU tersebut seperti misalnya mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video, mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual, mengunggah foto, menyebarkan informasi.
Peraturan menteri ini bukanlah UU sehingga tidak perlu kekhawatiran berlebihan karena ia tidak berlaku sebagai aturan khusus kecuali sebagai acuan bagi peraturan lain di lingkungan Perguruan Tinggi (vide Pasal 2 huruf a). Apalagi sudah ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur soal kekerasan dan/atau kejahatan seksual secara umum. Jadi jangan hanya terpaku pada Pemendikbudristek tersebut sehingga seolah-olah hanya itulah aturan main tentang kekerasan seksual, quad-non - padahal tidak.
*)Agung Pramono, SH., CIL adalah seorang advokat, anggota Kongres Advokat Indonesia Pimpinan TSH.
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |